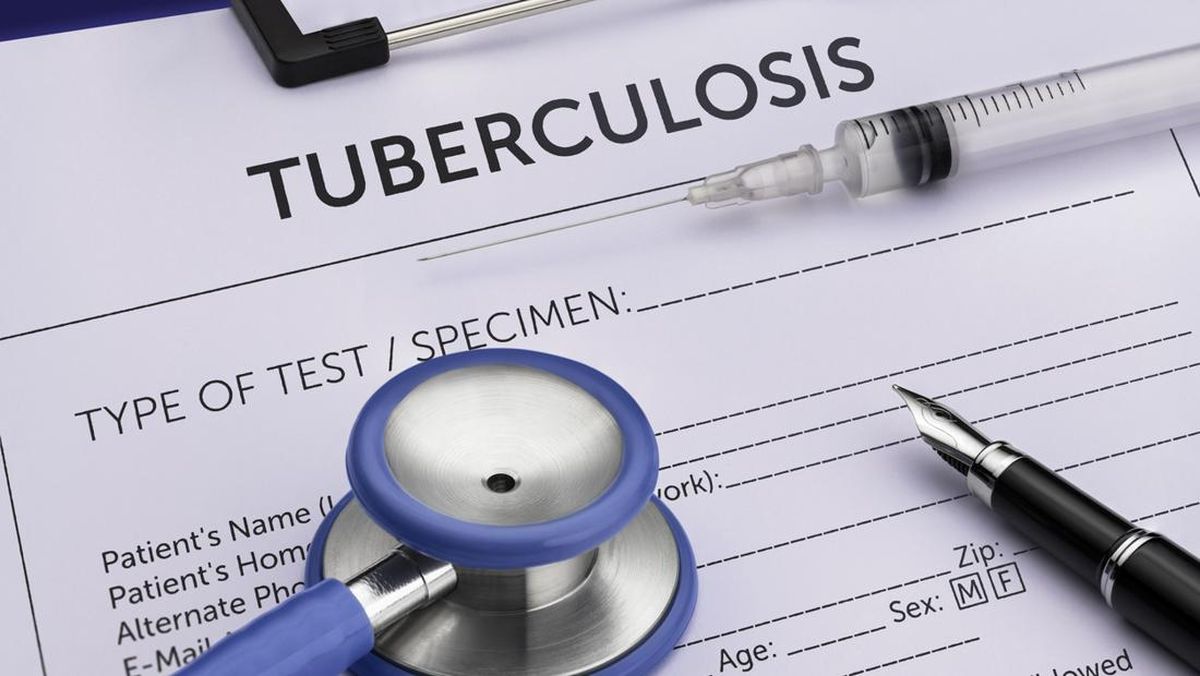Bencana dan Kegagalan Media Memberitakan Krisis Iklim
Seperti apa rasanya hampir sebulan rumah direndam banjir dan belum ada tanda air akan menyurut? Di Sintang, Kalimantan Barat, pertanyaan ini bisa diajukan pada sekitar 125 ribu orang yang sebagian besar mengungsi karena ketinggian air masuk rumah antara puluhan senti hingga dua meter.
Situasi serupa meluas ke Kalimantan Tengah, Selatan dan menurut peringatan BMKG terbaru, kemungkinan akan merembet pula ke Kalimantan Utara.
Musim hujan masih akan berlangsung sedikitnya 3 bulan lagi dan banjir–ditambah longsor, petir, pohon tumbang, angin puting beliung dan rob–dipastikan akan terjadi pula di Sumatera (Aceh Timur mulai banjir, di Serdang Bedagai Sumatera Utara, banjir memasuki pekan kedua), Papua (banjir bandang dan longsor di Yapen dan Nabire sudah duluan terjadi September lalu), dan tentu, di Jawa.
Media arus utama hampir seluruhnya menjadikan berita bencana hidrometeorologi ini sebagai headline, tetapi sedikit yang menyandingkannya langsung dengan isu perubahan iklim, seolah-olah peristiwa-peristiwa ini muncul begitu saja karena musim berubah.
Berbagai studi menunjukkan bahwa munculnya cuaca ekstrem termasuk hujan dengan kelebatan luar biasa, bermacam topan dan siklon yang makin sering muncul, disebabkan oleh iklim bumi yang berubah.
Ketika diadu dengan daya dukung lingkungan yang menipis, Indonesia nampak tinggal menunggu saat untuk jadi lokasi bencana.
Rentetan panjang penjelasan dari mana asal bencana dan kenapa terjadi makin sering, mestinya adalah salah satu cara ‘terdekat’ memberitakan fenomena perubahan iklim untuk audiens nusantara. Sampai seorang teman dari negara asing pernah bertanya: apakah isu perubahan iklim sudah jadi topik mainstream di Indonesia? Apakah media mengangkatnya setiap hari?
Dua tahun lalu ketika pertanyaan itu diajukan, saya jawab tidak. Isu bencana sudah jadi menu pemberitaan utama sejak puluhan tahun di Indonesia. Biasanya bencana dikaitkan dengan ‘perubahan musim’ seperti banjir dan longsor saat penghujan dan kekeringan parah pada kemarau.
Mengubah narasi ini menjadi bencana ‘sebagai dampak perubahan iklim’ masih jarang dilakukan media. Mungkin karena perlu penjelasan lebih teknis bagaimana bencana yang sudah puluhan tahun menjadi bagian dari fenomena alam tiba-tiba disangkutpautkan dengan perubahan iklim, atau singkatnya: “perubahan iklim apa sih, dari dulu juga sudah sering ada bencana. Namanya juga musibah…”
|
|
Komunikasi isu iklim diidentifikasi Badan PBB untuk perubahan iklim, UNFCC, sebagai salah satu isu paling krusial dalam pencapaian target menghindari krisis. Gagal dalam komunikasi bisa berdampak pada bencana iklim yang makin besar. Komunikasi semacam ini perlu pengetahuan dan kesabaran.
Pengetahuan karena perubahan iklim adalah persoalan ilmiah.
Konsepnya rumit untuk sebagian besar orang sehingga semua perlu belajar, termasuk/terutama wartawan. Ini bukan persoalan Indonesia saja, berbagai studi menyatakan kerumitan konsep adalah salah satu hambatan utama komunikasi iklim dunia.
Bagaimana menjelaskan perubahan iklim adalah penyebab banjir dan bukan sekedar hujan yang turun dua hari terus-menerus, misalnya.
Kenapa kenaikan suhu dipatok kurang dari dua derajat, kenapa wilayah kepulauan yang paling rentan, kenapa mesti ada komitmen penghentian deforestasi, dan seterusnya.
Juga apa arti efek rumah kaca, FoLU net sink, jejak karbon, Protokol Kyoto, dan lain-lain. Bagaimana membuat terjemahan yang sederhana dan mudah dimengerti adalah persoalan berikutnya.
Sementara kesabaran diperlukan untuk menjelaskan istilah dan jargon teknis itu dalam materi liputan sehari-hari, terus-menerus hingga persepsi publik terbentuk.
Di tengah isu yang lebih menarik–korupsi, balapan sirkuit baru, baliho capres, artis jadi Ketua RT–isu perubahan iklim sering kalah dalam ‘nilai jual’, miskin klik dan karena itu, sepi pengiklan.
Namun jebakan yang paling sulit dihindari media adalah pemberitaan yang bertumpu pada peran pejabat dan agenda seremonial. Ini nampak dari laporan media tentang COP26 di Glasgow lalu.
|
|
Meski konteks dan setting acara memang pertemuan para pembesar dunia, sudut pandang memberitakan selama berhari-hari meneguhkan anggapan bahwa iklim adalah isu elit.
Di layar televisi kita, sampai hari ini, perdebatan soal iklim hampir 100 persen diwakili oleh kelompok-kelompok ini: pejabat versus pegiat/LSM.
Tengok perdebatan paling hangat akhir-akhir ini soal pembabatan hutan, tokohnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Greenpeace.
Sedikit narasi yang memasukkan petani, nelayan atau warga kampung banjir sebagai penyandang suara utama dalam diskursus iklim.
Studi Tim Komunikasi Universitas Florida menunjukkan orang mendengarkan orang lain “seperti mereka”–artinya kalau isu iklim diwakili oleh wajah elit, sangat mungkin warga kebanyakan tak menganggap isu iklim perlu mendapat perhatian, karena toh sudah diurus oleh “orang-orang besar”.
Banjir dan rob akhirnya diterima sebagai bagian kenyataan hidup dan karena itu, langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim makin jauh dari sasaran.
Ketidaktahuan soal isu iklim berubah jadi apatisme alias pasrah terima nasib meski bencana terus datang. Sementara di tangan politisi dan kepentingan politik, alih-alih berkembang jadi target adaptasi iklim, isu bencana kemudian jadi alat untuk saling menjatuhkan lawan.
Amatan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim beberapa hari lalu soal sistem pendidikan Indonesia yang gagal membangun kesadaran siswa dan orang tua tentang iklim, mungkin juga merupakan cerminan dari kegagalan media menampilkan isu iklim pada audiensnya.
Tentu saja masih banyak hal yang bisa dilakukan media untuk memperbaiki situasi ini. Opsi teratasnya adalah dengan memperbanyak pemberitaan isu iklim. Targetnya menyambungkan isu sehari-hari; cuaca, bencana, kenaikan angka prostitusi, TKI ilegal, sebagai bagian dari isu iklim.
Framing “semua berkaitan dengan iklim” penting diterjemahkan dalam pesan media sehingga seperti pada isu Covid-19, lambat laun muncul konsensus bersama tentang krisis iklim dan bagaimana menghadapinya.
|
|
Kedua, mengembalikan peran (agency) dalam isu iklim pada rakyat. Isu iklim bukan sekedar isu lingkungan tetapi isu keadilan dan HAM; yang paling banyak jadi korban adalah yang terendah posisinya dalam rantai produksi dan kesejahteraan.
Konstitusi menjamin hak warga negara atas sandang, pangan, papan, tiga isu pertama dalam krisis iklim.
Anak-anak yang diperjualbelikan dalam rantai perdagangan manusia banyak berasal dari daerah tandus yang makin kekurangan air akibat krisis iklim.
Angka kemiskinan juga bertambah karena hasil panen gagal akibat cuaca yang terlalu esktrem. Sebaliknya buangan karbon yang menyebabkan iklim berubah disumbang antara lain oleh pabrik, pembangkit listrik dan kendaraan pribadi yang mayoritas dimiliki orang kaya.
Jika jurnalisme kerap diartikan sebagai penyambung lidah kelompok tak bersuara (voice of the voiceless) menempatkan para tokoh ini dalam pemberitaan adalah tugas penting media.
(stu)
LEBIH BANYAK DARI KOLUMNIS